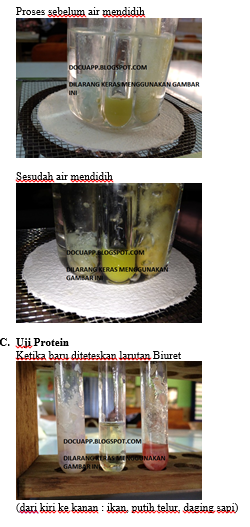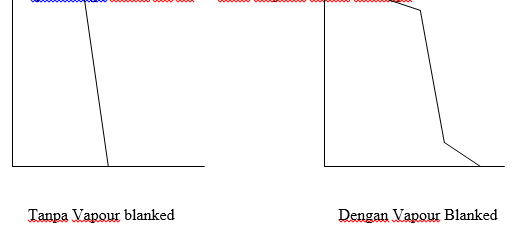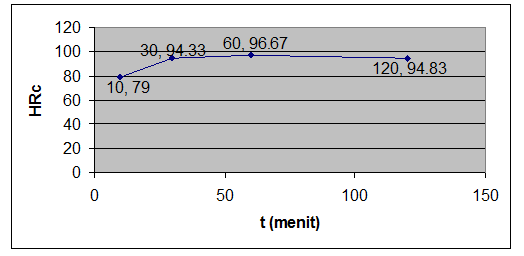I.
Judul :
Menguji Makanan
II.
Tujuan
Agar siswa
dapat mengetahui kandungan zat gizi (karbohidrat, amilum, protein, lemak) pada
berbagai bahan makanan
III.
Dasar Teori
Pencernaan adalah
sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat,
dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi
nutrisi. Pencernaan terjadi pada organisme multi sel, sel, dan tingkat sub-sel,
biasanya pada hewan.
Pencernaan
biasanya dibagi menjadi aktivitas mekanik dan kimia. Dalam kebanyakan
vertebrata, pencernaan adalah suatu proses banyak-tingkat dalam sebuah sistem
pencernaan, setelah ingesti dari bahan mentah, kebanyakan organisme lain.
Proses ingesti biasanya melibatkan beberapa tipe manipulasi mekanik.
Pencernaan
dibagi menjadi lima
proses terpisah:
1. Injesti: Menaruh makanan di mulut
2. Pencernaan mekanik:
Mastikasi, penggunaan gigi untuk merobek dan menghancurkan makanan, dan
menyalurkan ke perut.
3. Pencernaan kimiawi:
Penambahan kimiawi (asam, 'bile', enzim, dan air) untuk memecah molekul
kompleks menjati struktur sederhana
4. Penyerapan: Gerakan nutrisi
dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan 'lymphatic capallaries' melalui
osmosis, transport aktif, dan difusi
5. Penyingkiran: Penyingkiran
material yang tidak dicerna dari 'tract' pencernaan melalui defekasi.
Di belakang
proses tersebut adalah gerakan otot di seluruh sistem deglutisi dan
peristalsis.
IV.
Alat dan
Bahan
1.
Alat :
a.
Mortar
b.
Pistil
c.
Tabung reaksi
d.
Pengaduk
e.
Pembakar spiritus
f.
Korek api
g.
Kertas koran
h.
Papan tes porselen
i.
Gelas beker
j.
Rak tabung reaksi
k.
Gelas ukur
l.
Cawan petri
2.
Bahan :
a.
Akuades (air)
b.
Larutan lugol
c.
Fehling A dan B
d.
Larutan Biuret
e.
Gula
f.
Roti
g.
Nasi
h.
Terigu
i.
Ubi
j.
Putih telur
k.
Daging
l.
Ikan
m.
Mentega/margarine
n.
Sirup
V.
Cara Kerja
A.
Uji Amilum
1.
Siapkan bahan makanan yang akan diuji (terigu, ubi).
2.
Haluskan setiap bahan makanan dengan menggunakan mortar
dan pinsil, lalu tambahkan sedikit akuades.
3.
Masukkan hasil cara kerja nomor 2 pada tabung reaksi.
Catatlah setiap bahan makanan atau difoto!
4.
Teteskan larutan lugol sebanyak 5 tetes pada setiap
bahan makanan tersebut!
5.
Amatilah perubahan warna yang terjadi pada setiap bahan
makanan. Jika bahan makanan mengandung amilum, warna pada bahan makanan akan
menjadi biru sampai hitam.
6.
Fotolah hasil akhir dari pengamatan!
B.
Uji
Karbohidrat
1.
Siapkan bahan makanan yang akan diuji (gula, roti,
nasi).
2.
Haluskan setiap bahan makanan dengan menggunakan mortar
dan pinsil, lalu tambahkan sedikit akuades.
3.
Masukkan hasil cara kerja nomor 2 pada tabung reaksi.
Catatlah setiap bahan makanan atau difoto!
4.
Tetesi gula dan nasi dengan menggunakan larutan
Bennedict sebanyak 5 tetes, sedangkan pada roti ditetesi dengan Fehling A dan B
masing-masing sebanyak 3 tetes.
5.
Masukkan ketiga tabung reaksi yang telah berisi bahan
makanan tersebut ke dalam gelas beker yang telah terisi air yang dibakar dengan
menggunakan pembakar spiritus.
6.
Amatilah perubahan warna yang terjadi pada setiap bahan
makanan. Jika bahan makanan mengandung karbohidrat, warna pada bahan makanan
akan menjadi biru, lalu berubah menjadi hijau sampai merah bata.
7.
Fotolah hasil akhir dari pengamatan!
C.
Uji Protein
1.
Siapkan bahan makanan yang akan diuji (putih telur,
daging, ikan).
2.
Haluskan setiap bahan makanan dengan menggunakan mortar
dan papan tes porselen serta pinsil, lalu tambahkan sedikit akuades (khusus
untuk putih telur, tidak perlu ditambahkan akuades).
3.
Masukkan hasil cara kerja nomor 2 pada tabung reaksi.
Catatlah setiap bahan makanan atau difoto!
4.
Tetesi bahan makanan dengan menggunakan larutan Biuret
sebanyak 5 tetes.
5.
Amatilah perubahan warna yang terjadi pada setiap bahan
makanan. Jika bahan makanan mengandung protein, warna pada bahan makanan akan
menjadi ungu.
6.
Fotolah hasil akhir dari pengamatan!
D.
Uji Lemak
1.
Siapkan bahan makanan yang akan diuji (mentega, sirup).
2.
Oleskan bahan makanan tersebut pada kertas koran dan
keringkan kertas tersebut.
3.
Amatilah perubahan yang terjadi. Jika mengandung lemak,
maka kertas minyak akan tampak transparan.
4.
Fotolah hasil akhir dari pengamatan!
VI.
Hasil
Pengamatan
|
No.
|
Uji
|
Hasil Praktikum
|
Hasil sebenarnya
|
|
1.
|
Uji Amilum
·
Terigu + Lugol
·
Ubi + Lugol
|
·
Biru kehitaman
·
Biru kehitaman
|
Biru kehitaman
|
|
2.
|
Uji Karbohidrat
·
Gula + Bennedict
·
Roti + Fehling A dan B
·
Nasi + Bennedict
|
·
Kuning
·
Kuning tua
·
Putih dan Kuning
|
Merah
Bata
|
|
3.
|
Uji Protein
·
Ikan + Biuret
·
Putih telur + Biuret
·
Daging sapi + Biuret
|
·
Ungu
·
Bening + Ungu
·
Merah tua
|
Ungu
|
|
4.
|
Uji Lemak
·
Sirup
·
Mentega
|
|
Transparan
|
Pada praktikum
uji karbohidrat, yang paling cepat berubah warna adalah gula, diikuti dengan
roti, dan nasi.
Foto-foto
praktikum:
VII. Kesimpulan
Dalam melakukan
uji makanan, diperlukan berbagai proses tertentu sesuai dengan bahan makanan
yang akan diujikan. Untuk menguji amilum dengan menggunakan larutan lugol, dan
hasil akhir yang didapat ada;ah biru kehitaman. Untuk menguji karbohidrat, dilakukan
dengan pemanasan dan larutan Bennedict, hasil akhir yang didapat adalah merah
bata. Uji protein dengan larutan biuret dan didapat warna ungu, dan uji lemak
menggunakan kertas koran yang akan menyebabkan kertas koran menjadi transparan.
(Hasil penetesan larutan ini akan menghasilkan warna yang berbeda-beda)